MUDANEWS.COM
A. Pendahuluan
Belakangan ini ramai kalangan membicarakan kebangkitan semangat beragama masyarakat Indonesia, yang ditandai dengan meningkatnya dedikasi pemeluk agama terhadap ajaran agamanya, seperti makin rajinnya pemeluk agama datang ke rumah-rumah ibadah mereka, khususnya umat Islam yang semakin gencar menyemarakkan dan memakmurkan masjid tidak hanya dalam menegakkan shalat lima waktu, termasuk shalat Jumat, tetapi juga berbagai kegiatan keagamaan dan keummatan lainnya.
Demikian juga dapat dilihat, misalnya, bagaimana kelompok kelas menengah umat Islam perkotaan yang bersemangat menghadiri berbagai majelis ta’lim, zikir akbar, dan lain-lain yang tidak hanya dilakukan oleh pihak-pihak swasta tetapi juga oleh kalangan pemerintah.
Kebangkitan semangat beragama ini menjadi fenomena menarik karena terjadi persis ketika orang berfikir bahwa kekuatan rasional (rational forces) sains dan teknologi telah berhasil menepikan misteri spiritual (spiritual mystery) dari kerangka berfikir manusia moderen, dan ketika manusia moderen mulai sadar bahwa kecukupan materi tidak dapat memenuhi kebahagian manusia, maka pada saat itulah justru kebangkitan semangat beragama mendapatkan momentumnya.
Namun demikian, satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa salah satu realitas yang menonjol dari fenomena kebangkitan beragama tersebut adalah menguatnya gerakan keagamaan yang mempunyai karakter fundamental-radikal yang mengusung simbol-simbol militansi agama yang kental yang dialami oleh semua agama dan terjadi hampir di setiap wilayah dunia, sebagaimana juga yang terjadi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga gerakan keagamaan ini banyak didominasi oleh kelompok Islam.
Gerakan keagamaan yang bersifat radikal ini (Islam radikal) juga telah menjadi fenomena penting yang turut mewarnai citra Islam kontemporer Indonesia, sebagaimana kita lihat dalam beberapa waktu terakhir adanya kelompok yang mengatas-namakan pembela Islam bergerak untuk menutup tempat-tempat yang mereka anggap sebagai sarang maksiat. Mereka tidak saja melakukan demonstrasi besar-besaran di berbagai tempat, akan tetapi juga, dalam beberapa kesempatan, menggunakan cara-cara yang boleh dikatakan keras, seperti menghancurkan tempat-tempat maksiat untuk menunjukkan sikap penolakan mereka. Sebagian dari kelompok radikal Islam ini tidak hanya melawan kerusakan nilai-nilai moralitas tetapi juga ingin menegakkan syariat Islam sebagai agenda mendirikan negara Islam Indonesia.
Lebih jauh, kelompok-kelompok radikal tersebut telah pula sampai pada upaya memerangi sesama umat Islam yang berbeda dalam metode atau aliran dalam berkeislaman, sebagaimana yang pernah dialami oleh kelompok Ahmadiyah dan Syiah di pulau Jawa dan Madura berapa waktu terakhir.
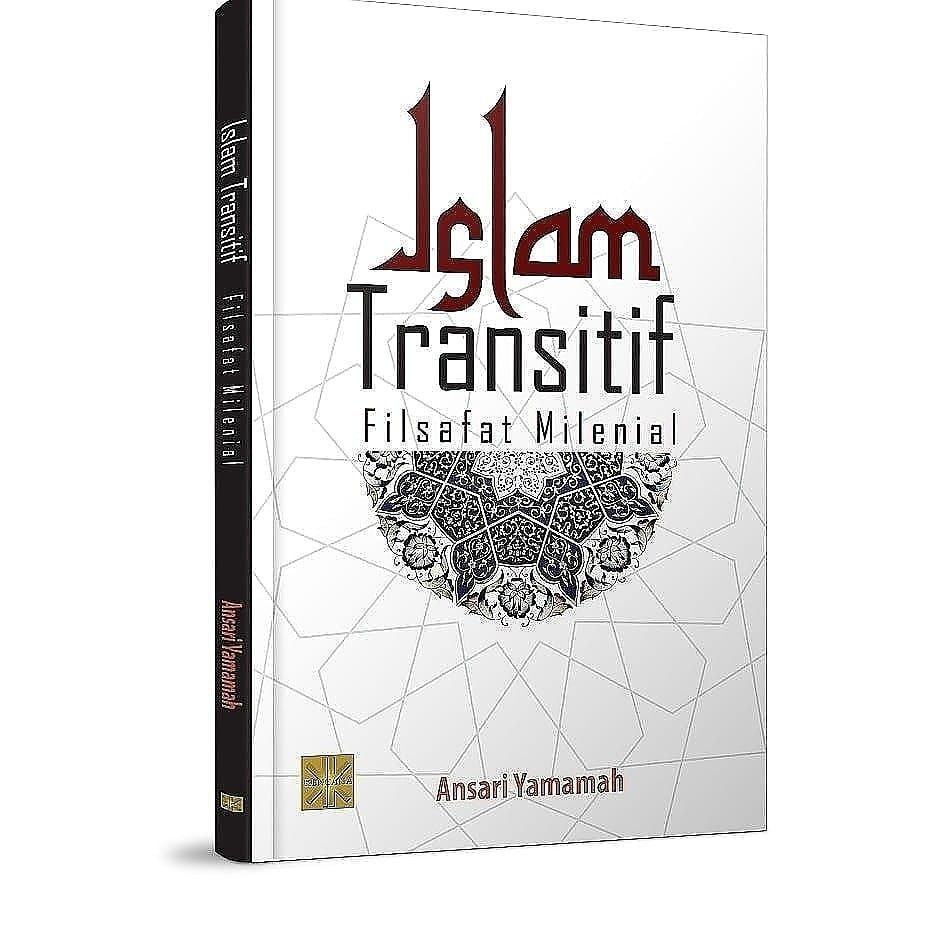
B. Pemicu Tumbuhnya Radikalisme Islam (di Indonesia)
Fakta yang ada tidak dapat disembunyikan bahwa pemahaman sempit, kaku, fanatis, dan keras, misalnya dikalangan kelompok Salafi Jihadis dan aliansinya, mempunyai faktor-faktor pemicu sehingga menjadikan mereka berfaham radikal dan sekaligus ultra revolutionist, yang antara lain berupa faktor:
1. Faktor internal keberagamaan: yang secara khusus terkait dengan pemahaman dan interpretasi terhadap konsep-konsep dasar Islam dan konsep-konsep perjuangan, seperti konsep jihad yang dipahami oleh kelompok radikal Islam yang tidak hanya sebagai bentuk perjuangan dakwah Islam, tetapi lebih jauh dipahami sebagai bentuk perlawanan (perang) terhadap musuh-musuh idelogis Islam (kaum kafir). Selain pemahaman dan penekanan dimensi teologisnya, jihad juga dibenturkan dalam dimensi dua kutub teritorial yang berseberangan yakni dār al-Islam dan dār al-harb yang mana dār yang kedua dijadikan sebagai sasaran ekspansi dengan legitimasi jihad untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi baik dengan cara damai ataupun perang.
2. Faktor eksternal sosio-politikultural: hegemoni politik, ekonomi dan budaya Barat (non Islam) terhadap umat Islam yang dianggap membahayakan Islam dan umat Islam. Bagi kalangan fundamentalis ide-ide modernisme Barat dianggap telah mendistorsi tradisionalisme mereka. Ketika ide-ide modernisme memasuki ranah kehidupan dan ideologi umat Islam maka harus dilakukan upaya-upaya membendung modernisme karena akan membuat ide-ide tradisional fundamentalis mereka akan menjadi menguat dan mempunyai daya tarik tersendiri, bahkan beberapa penulis melihat bahwa faktor ekonomi, alam yang gersang, dan semacamnya menjadi pemicu munculnya ekspresi gerakan fundamentalisme dalam bentuk perang suci dengan menaklukkan wilayah lain.
3. Faktor Psikologis: Melalui efikasi radikal dan agresif, yang dalam psikologi politik atau gerakan sosial, seseorang merasa bahwa dirinya penting, punya kemampuan, dan berarti untuk melakukan sesuatu yang diharapkan. Ada optimisme di situ yang merupakan energi psikologis pendorong (psychological driving force) suatu tindakan, yang dalam konteks politiknya dijadikan sebagai konteks aktivitas islamis (Islam gerakan – the Islamists). Faktor psikologis ini paling tidak terlihat dalam dua bentuk, yaitu:
• Alienasi radikal, suatu perasaan terasing seseorang dari lingkungannya. Apa yang terjadi di sekitar lingkungan kehidupannya bertentangan dengan apa yang diyakininya sebagai sesuatu yang harus terjadi. Perasaan alienasi radikal ini pada gilirannya akan berkembang menjadi aktivitas radikal. Perbedaan antara yang diyakininya dengan realitas yang dihadapinya (das sein dan das sollen) dapat terlihat dalam Islam sendiri dengan keyakinan melalui ayat-ayat Alquran yang menyatakan bahwa umat Islam adalah umat terbaik sedangkan dalam realitasnya, terutama dalam kehidupan dunia moderen sekarang, fakta yang muncul menunjukkan bahwa umat Islam masih jauh dari apa yang diharapkan. Kontradiksi antara das sein dan das sollen ini berpotensi menumbuhkan perasaan apologetik untuk menyalahkan kekuatan di luar Islam, karena merasa umat Islam diperlakukan tidak adil, bahkan ditindas dan dimarjinalkan. Konsekuensinya mendorong seseorang menjadi aktivis radikal sebagai wujud protes atas ketidakadilan yang dilakukan oleh kekuatan di luar Islam, termasuk kekuatan negara atau pemerintah yang mereka anggap juga telah keluar dari nilai-nilai Islam.
• Perasaan keputusasaan apolegetik (apologetic hopeless), sebuah perasaan putus asa yang mencoba mencari sesuatu yang lain untuk dijadikan alasan sumpah serapah (scapegoating) dalam rangka melegitimasi keputusasaannya di hadapan orang lain.
4. Dendam Politikultur: Munculnya gerakan reformasi Islam di beberapa negara-negara Arab ketika berakhirnya Kerajaan Turki yang mana gerakan ini berusaha untuk memurnikan ajaran-ajaran dan praktek keagamaan umat Islam yang sekian lama terpengaruh oleh hegemoni kultur Barat yang mereka anggap sebagai budaya setan (evil cultur). Hegemoni ini tentu tidak terlepas dari kekuatan politik Barat yang hari ini telah mengalahkan kekuatan politik dunia Islam. Oleh karenanya kultur Barat haruslah dijauhi dan dianggap sebagai musuh, dan mereka harus diperangi sebagai balasan atas penindasan mereka terhadap umat Islam. Gerakan yang sama muncul juga di beberapa daerah Islam lainnya, seperti Gerakan Salafi yang menjadi representasi Wahabisme, Gerakan Mahdi di Sudan, Gerakan Sanusi di Afrika Utara, dan juga termasuk Gerakan Persatuan Islam di Indonesia.
5. Faktor Sejarah: sejak Abad Kegelapan hingga Abad Pertengahan, upaya-upaya untuk menaklukkan dan mengalahkan bangsa/masyarakat yang lemah merupakan bagian dari kebiasaan suatu bangsa atau kerajaan yang lebih kuat, sehingga kebiasaan tersebut dan seluruh akibatnya dapat diterima secara sah menurut pandangan politik dan hukum bangsa-bangsa pada masa itu. Fakta membuktikan betapa banyak sistem hukum dan kerajaan yang membenarkan praktek aneksasi tersebut, seperti hukum Yunani, Romawi, Bizantium, dan kerajaan kaum Frank, kerajaan Visighot, Ostrogoth, Mongol, negara-negara tentera salib, dan lain sebagainya yang saling menginvasi dalam kompetisi tiada henti demi untuk merebut kekuasaan dan mengokohkan dominasi dan hegemoni, termasuk apa yang dilakukan oleh kekhalifahan-kekhalifahan Islam awal. Realitas sejarah ini tentu saja berpengaruh pada pembentukan hukum Islam yang dimulai sejak abad ke 2 H atau abad ke 8 M dimana para ahli hukum (fuqaha) banyak memasukkan berbagai logika realitas sosial, politik dan ekonomi pada masanya ke dalam interprestasi-interprestasi yang mereka lakukan terhadap Alquran dan hadis Nabi. Praktek-praktek kebenaran yang pada awalnya memang murni untuk kebaikan, namun kemudian berubah menjadi kebenaran yang digunakan untuk kejahatan (kebatilan) yang pada gilirannya melahirkan ilmu retorika bias politik yang dikuasai oleh kekhalifahan atas kepentingan relasi politik dan ekonomi. Dari sinilah lahir panji-panji palsu yang menggantungkan segala sesuatu kepada kepastian qadha dan qadhar secara artifisial dengan merubah konsep jihad menjadi perang eksternal dan penaklukan melalui ekspansi militer dan kekuatan senjata dengan cara membunuh pelaku makar hukum, dan mengarahkan peperangan eksternal atas nama jihad dan dakwah. Lebih jauh, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Syahrur bahwa retorika politik ini semakin kokoh dalam bentuknya yang mutakhir, dimulai dari Usman bin Affan (576-656H) dengan pernyataanya: “Aku tidak akan melepaskan ‘baju’ yang dipakaikan Allah kepadaku …”, dan kemudian diteruskan oleh para khalifah-khalifah Islam lainnya, seperti Abdullah bin Marwan (646-705M) yang menyatakan: “Saya tidak ingin mendengar seseorang yang berkata kepadaku ‘bertakwalah kepada Allah’, kecuali akan kupukul tengkuknya”; dan Abu Ja’far al-Manshur (95-158H/714-775M) serta khalifah-khalifah sesudahnya yang memegang semboyan bahwa: “Sesungguhnya kami menghakimi kalian dengan kekuasaan Allah.” Oleh karena itu, mereka mau tidak mau harus mengalihkan konflik internal menuju wilayah eksternal atas nama jihad. Dalam tradisi kerajaan Islam di Indonesia juga didapati berbagai istilah atau gelar berbau teologis yang diberikan kepada seorang raja ataupun sultan, seperti gelar zhillulah fi al-ardh, sehingga raja dianggap memiliki legitimasi ketuhanan untuk menentukan ataupun memberlakukan hukum dan kebijakan politik.
Bersambung…
Oleh: Ansari Yamamah
Penulis adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, dan ketua Pusat Kajian Deradikalisasi UIN Sumatera Utara.


