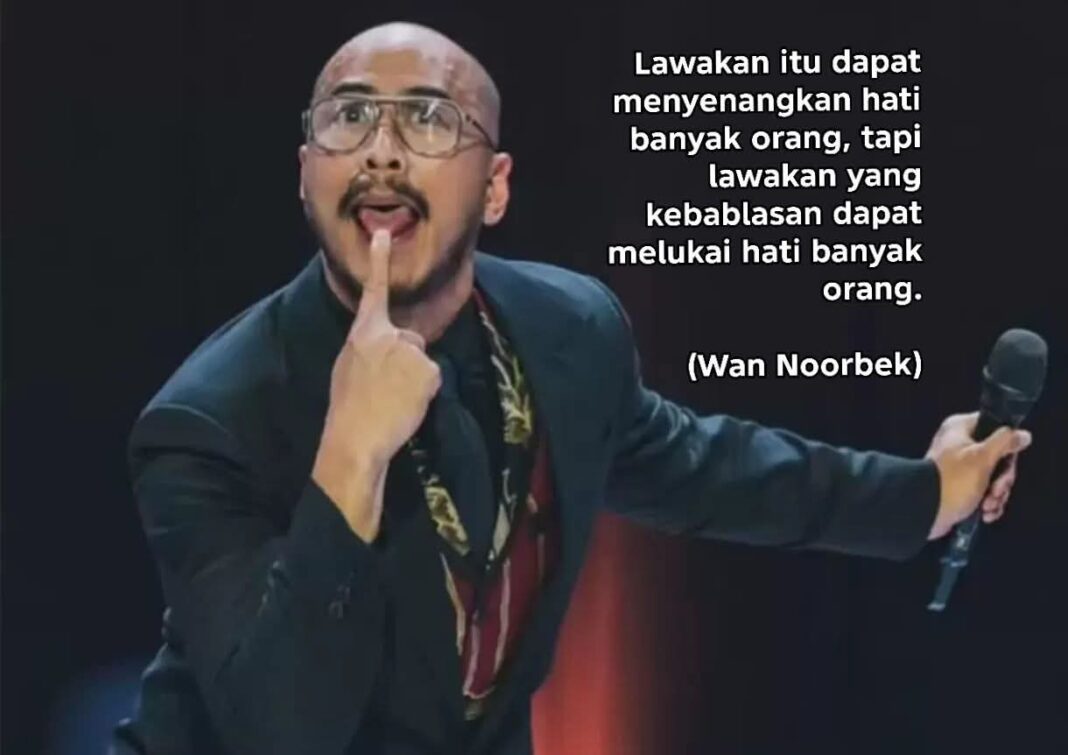Oleh: Nur Shollah Bek
Mudanews OPINI Humor dan seni pertunjukan, termasuk stand up comedy, kerap diposisikan sebagai ruang kebebasan berekspresi. Dalam teori demokrasi modern, kebebasan berekspresi memang merupakan hak fundamental warga negara yang dijamin konstitusi. Namun, dalam perspektif ilmu hukum, tidak ada satu pun hak yang bersifat absolut. Setiap kebebasan selalu berkelindan dengan batas, tanggung jawab, serta konsekuensi hukum.
Lawakan tidak otomatis mencerminkan kecerdasan. Terlebih apabila materi yang disampaikan tidak lagi berfungsi sebagai kritik sosial yang konstruktif, melainkan berubah menjadi sarana menyinggung, mengolok-olok, dan merendahkan keyakinan agama, identitas kelompok, atau pilihan politik orang lain. Dalam konteks ini, humor kehilangan nilai etiknya dan justru menjelma sebagai bentuk kebodohan yang disengaja—karena sadar akan dampaknya, namun tetap diproduksi demi sensasi dan popularitas.
Secara teoritik, hukum pidana modern—termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)—dibangun atas asas perlindungan kepentingan hukum (rechtsbelangen). Agama, kehormatan pribadi, dan ketertiban umum merupakan kepentingan hukum yang wajib dilindungi negara. Oleh karena itu, ekspresi yang mengandung penistaan agama, pencemaran nama baik, maupun ujaran kebencian tidak dapat berlindung di balik dalih seni, satire, atau kebebasan berekspresi semata.
Dalam UU ITE, substansi hukum tidak menilai “niat melucu”, melainkan akibat hukum dari konten yang disebarkan. Ketika sebuah materi stand up atau konten media sosial:
1. Merendahkan simbol dan praktik ibadah agama tertentu,
2. Menyerang kehormatan individu atau kelompok tanpa dasar kepentingan publik yang sah,
3. Memicu kebencian, permusuhan, atau polarisasi sosial,
maka unsur-unsur delik telah terpenuhi secara yuridis, terlepas dari panggung seni atau format hiburan yang digunakan.
Teori fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) menegaskan bahwa hukum bukan sekadar teks normatif, melainkan instrumen untuk menjaga keseimbangan sosial. Jika undang-undang hanya diperlakukan sebagai saduran formal tanpa keberanian penegakan, maka hukum kehilangan wibawa, keadilan berubah menjadi ilusi, dan konflik horizontal menjadi keniscayaan.
Lebih jauh, pembiaran terhadap penghinaan berbasis agama dan identitas melalui panggung komedi maupun media sosial akan menciptakan preseden berbahaya: seolah-olah ruang digital dan seni adalah wilayah bebas nilai dan bebas hukum. Padahal, dalam negara hukum (rechtstaat), tidak ada ruang yang kebal dari pertanggungjawaban hukum.
Kritik sosial yang cerdas lahir dari argumentasi, data, dan etika. Satire yang bermartabat menertawakan kekuasaan, ketimpangan, dan kebijakan publik—bukan keyakinan suci yang menjadi fondasi batin jutaan orang. Ketika agama dan kehormatan dipermainkan, yang lahir bukan pencerahan, melainkan provokasi.
Maka pertanyaannya sederhana namun mendasar: buat apa undang-undang dibuat, jika tidak dijadikan sandaran dalam menegakkan keadilan? Jika hukum hanya hadir sebagai hiasan demokrasi tanpa keberanian untuk ditegakkan secara adil dan konsisten, maka yang tersisa hanyalah kekacauan yang dilegalkan oleh kelalaian.
Di sinilah pentingnya kesadaran kolektif—baik bagi seniman, kreator konten, penegak hukum, maupun masyarakat—bahwa kebebasan berekspresi bukan tiket untuk melukai, dan humor bukan pembenaran untuk menghina. Hukum hadir bukan untuk membungkam kreativitas, melainkan untuk memastikan bahwa kreativitas tidak berubah menjadi alat perusak harmoni sosial.
Nur Shollah Bek
Ketua Forum Ulama Nusantara