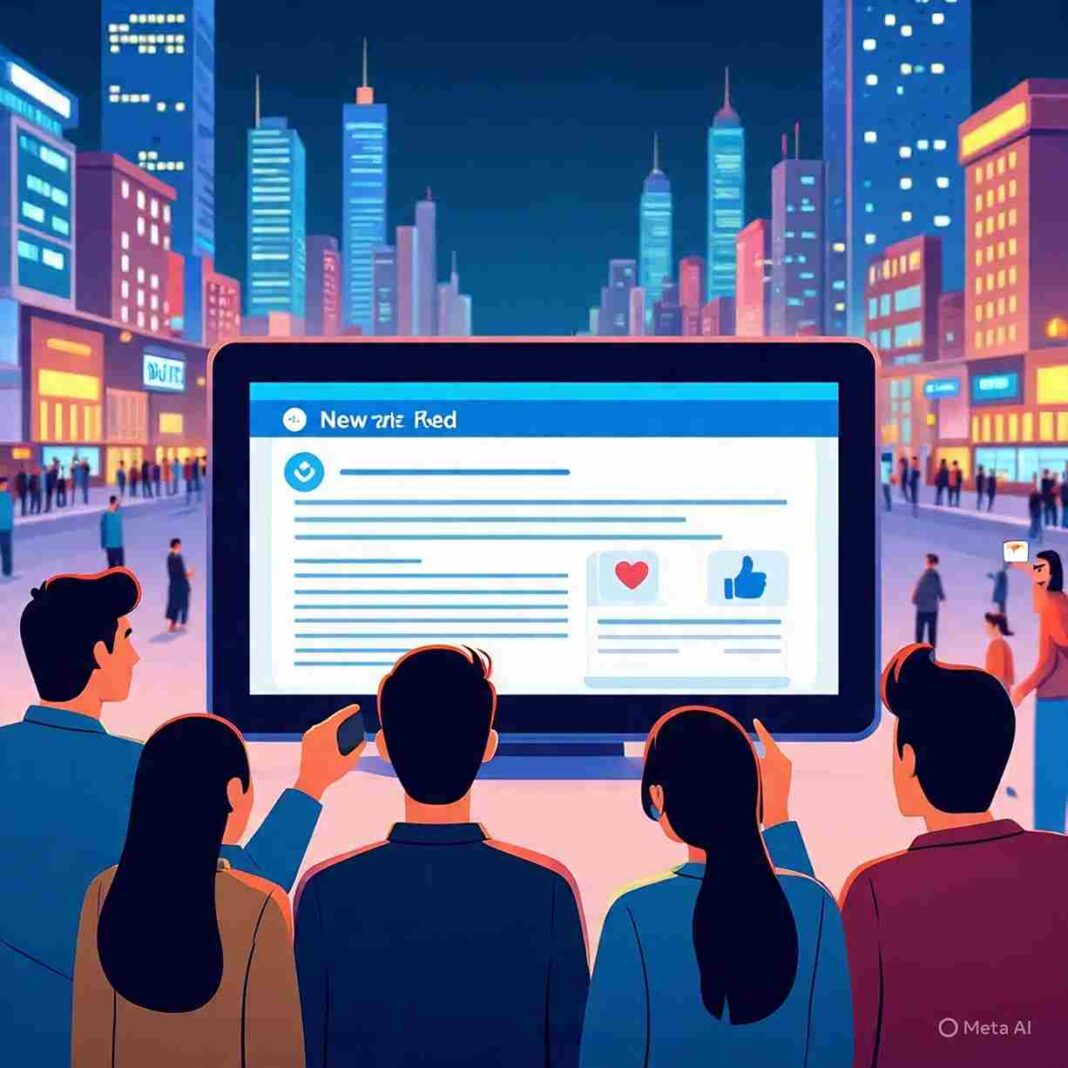Oleh : Rosadi Jamani Ketua Satupena Kalbar
Mudanews.com OPINI | Ada kawan dosen di Sulawesi Selatan kirim pesan di grup. Ia share empat koran ternama di Makassar, tidak satu pun memberitakan dugaan korupsi Halim Kalla. Sebagai orang Pantai Losari, ia merasa aneh. Saya iseng jawab, untung ada media sosial. Dalam hati, ini menarik. Yok, kita lindas, eh salah, kupas soal koran dan medsos sambil seruput kopi tanpa gula, daeng!
Saya sudah kupas soal Halim Kalla, sang pengusaha dan mantan politisi, kelahiran Makassar 1 Oktober 1957. Sosok ulet, berpendidikan Amerika, dan dulu dielu-elukan sebagai simbol kesuksesan. Tapi kini, namanya terseret dalam proyek PLTU 1 Kalimantan Barat yang katanya merugikan negara Rp1,35 triliun.
Anehnya, skandal korupsi sebesar itu, tak ada satu pun koran yang berani menulis. Sunyi. Hening. Seolah tinta mereka mendadak beku di tangan ketakutan. Padahal ini bukan kisah biasa, tapi berita bernilai triliunan. Namun rupanya, listrik bukan satu-satunya yang padam di negeri ini, kadang, nurani redaksi juga ikut padam.
Tapi tenang. Karena di saat mesin cetak tidur, netizen sedang bangun sambil rebahan. Di tangan mereka, jari-jemari menjadi senjata paling demokratis di dunia. Di atas kasur, di bawah selimut, sambil ngemil keripik, mereka mengetik kebenaran yang tak bisa dimatikan. Itulah revolusi paling malas tapi paling efektif sepanjang sejarah manusia, revolusi jempol.
Media sosial kini adalah mesin informasi, emosi, dan mobilisasi yang tak tertandingi. Ia bukan sekadar aplikasi, tapi semesta baru tempat kebenaran, kebohongan, cinta, dan amarah bercampur jadi satu. Tak perlu editor, tak perlu surat tugas, cukup sinyal dan keberanian. Informasi menyebar dalam detik, bukan jam. Satu video warga bisa mengguncang dunia, sementara redaksi masih sibuk menentukan angle berita yang “aman”.
Medsos ini seperti kafe besar tanpa pintu. Semua orang boleh bicara. Bahkan, yang tidak tahu pun boleh berpendapat (dan biasanya paling ramai). Tapi di situlah keindahannya. Karena kebenaran tak lagi dimonopoli oleh segelintir orang bersetelan jas di ruang redaksi ber-AC. Kini, kebenaran bisa lahir dari kamar sempit anak kos yang sinyalnya dua bar, tapi semangatnya dua ratus persen.
Lihat bagaimana isu-isu besar muncul pertama kali di medsos. Dari korupsi, kekerasan, hingga skandal elite, semuanya lahir dari unggahan rakyat kecil sebelum akhirnya diangkat media besar, itupun setelah viral. Kadang kita tertawa, yang seharusnya jadi pengawas kekuasaan malah menunggu “izin trending dulu”. Ironi yang indah dan menyedihkan sekaligus.
Jangan salah, kekuatan medsos sudah menumbangkan banyak hal, reputasi, karier, bahkan pemerintah. Di Nepal, kaum Gen Z mengguncang negara hanya lewat medsos. Di Indonesia, satu thread bisa lebih ditakuti dari surat panggilan KPK. Satu hashtag bisa membuat politisi kehilangan suara, dan satu video berdurasi 30 detik bisa membuat korporasi gemetar.
Inilah era di mana kebenaran tidak lagi dicetak, tapi dibagikan. Bukan di halaman depan koran, tapi di beranda ponsel. Di mana komentar lebih tajam dari editorial, dan emoji api 🔥 bisa lebih jujur dari seluruh tajuk rencana.
Silakan, wahai koran-koran, padamkanlah tinta kalian. Tutup halaman depan kalian dengan aman. Tapi ketahuilah, media sosial tak punya saklar. Ia menyala terus, digerakkan oleh jutaan rakyat yang menolak dibungkam, walau sambil rebahan.
Karena di zaman ini, bukan pena yang lebih tajam dari pedang. Tapi jempol. Selama masih ada sinyal, kebenaran tak akan pernah bisa kalian padamkan.
Pesan moralnya, jangan pernah berharap kebenaran bisa dikubur hanya karena koran bungkam. Sebab zaman telah berubah. Kini suara rakyat bukan lagi bergantung pada redaksi, tapi pada keberanian tiap jempol yang menolak diam. Ketika media arus utama terbelenggu kepentingan, medsos menjadi ruang liar tempat nurani mencari jalan pulang. Di sanalah kita belajar. Kebebasan tidak butuh izin cetak, hanya butuh keberanian untuk menekan tombol “kirim.”***